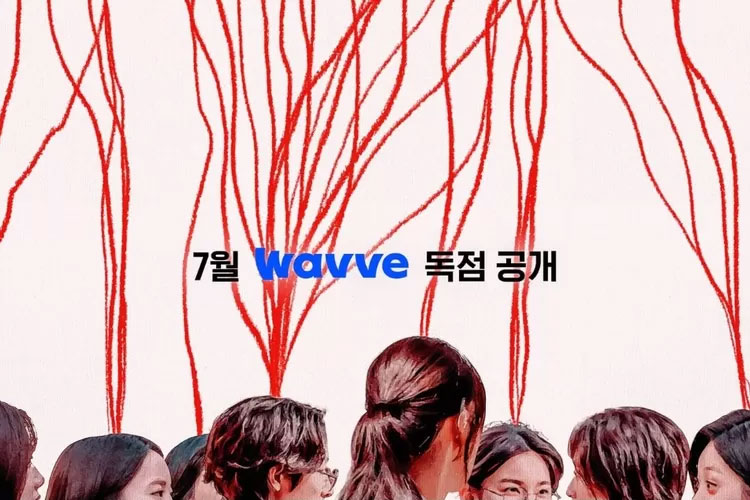TIMES JATIM, BONDOWOSO – Pengamat Hukum dari UIN KHAS Jember (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq) , Achmad Hasan Basri, menilai fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, sebagai bentuk nyata dari produk hukum yang berpihak pada kepentingan sosial dan moral masyarakat.
Menurut Hasan, kehidupan saat ini terus berkembang dalam berbagai bidang. Mulai dari teknologi, ekonomi, hukum hingga kesenian. Termasuk fenomena sound horeg, yaitu penggunaan sistem pengeras suara ekstrem dengan volume mencapai 135 desibel.
Perkembangan semacam ini, menurutnya, idealnya disandarkan pada ilmu pengetahuan demi kemaslahatan bersama.
“Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 MUI Jawa Timur menyatakan bahwa penggunaan sound horeg adalah haram. Apabila menimbulkan gangguan terhadap masyarakat, dampak kesehatan, perilaku maksiat, atau kerusakan lingkungan,” jelasnya.
Hasan menjelaskan, fatwa tersebut merupakan respons terhadap keluhan publik yang resah akibat maraknya penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan.
Seperti hajatan, pawai, dan kontes adu sound system. Ia menyebut, fatwa ini lahir dari metode penemuan hukum berbasis ilmu pengetahuan lintas disiplin.
Dalam perspektif hukum, Hasan mengaitkan fatwa ini dengan teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick.
“Hukum responsif adalah hukum yang terbuka terhadap nilai moral dan sosial, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Ciri utamanya bersifat partisipatif dan adaptif terhadap perubahan sosial,” paparnya, Rabu (23/7/2025).
Ia menilai bahwa fatwa MUI ini bersifat bottom-up, yaitu muncul dari keresahan masyarakat terhadap polusi suara dan gangguan ketertiban umum.
“Fatwa ini berfungsi preventif, membentuk kesadaran etik dan keagamaan. Ini adalah ciri khas hukum responsif yang tidak hanya menekankan sanksi, tetapi juga edukasi dan kesadaran kolektif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hasan juga mengaitkan fenomena sound horeg dengan prinsip-prinsip keadilan menurut teori John Rawls.
“Jika hanya menguntungkan pihak tertentu seperti penyewa atau pemilik sound. Namun merugikan masyarakat luas, seperti lansia, anak-anak, atau rumah ibadah. Maka itu bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls,” tegasnya.
Ia juga merujuk pada gagasan Aristoteles tentang keadilan distributif dan komutatif. Dimana ketika kebebasan satu pihak menyebabkan penderitaan pihak lain, maka itu tidak adil, baik secara distribusi manfaat maupun dalam relasi timbal balik.
Hasan mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) ikut berperan melalui regulasi formal, seperti Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum atau Lingkungan, yang dapat mengatur batas ambang suara secara jelas dan terukur.
Hasan menegaskan, bahwa fatwa haram terhadap sound horeg merupakan contoh nyata hukum yang hidup dan tumbuh dari nilai sosial, moral, dan keagamaan masyarakat.
“Ini adalah wujud dari hukum responsif yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial: menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif,” pungkasnya.(*)
| Pewarta | : Moh Bahri |
| Editor | : Imadudin Muhammad |