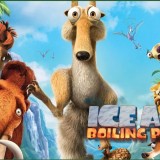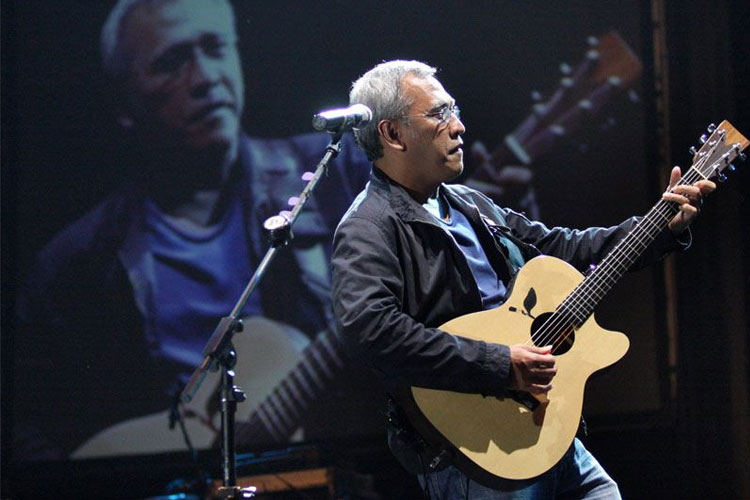TIMES JATIM, NGANJUK – Fenomena anarko baru-baru ini sering kali dikaitkan dengan perilaku demonstrasi yang dianggap radikal, destruktif, dan penuh perlawanan terhadap otoritas. Namun, untuk memahami anarko secara lebih mendalam, perlu ditinjau dari epistemologi filsafat anarkisme itu sendiri.
Anarkisme bukan sekadar ideologi perlawanan, tetapi sebuah kerangka berpikir yang berakar pada penolakan terhadap otoritas hierarkis, dominasi negara, dan segala bentuk penindasan struktural.
Banyak media massa yang secara jelas telah melakukan pendistorsian makna dari Anarkisme, hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat Indonesia anti terhadap Anarkisme, ditambah lagi media yang selalu menggiring opini publik untuk anti terhadap Anarkisme.
Coba lihat di beberapa media, jika ada berita tentang amuk massa yang mengakibatkan kerusakan langsung disebut sebagai “aksi anarkis”, ini akan berdampak sangat buruk apa lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia yang hasrat membaca dan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Tentu saja mereka akan mengandalkan ilmu dari apa yang mereka lihat dari media yang paling mudah diakses yaitu televisi dan media cetak.
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya framing negatif terkait Istilah Anarkisme dalam konteks masyarakat kontemporer di Indonesia sering dipahami secara sempit sebagai kelompok perusuh. Padahal, secara filosofis, anarkisme merupakan aliran pemikiran yang memiliki epistemologi sendiri terkait cara pandang terhadap pengetahuan, kebebasan, dan relasi kuasa.
Epistemologi Filsafat Anarkisme
Pada tahun 1923 Ir. Soekarno presiden pertama indonesia pernah menulis bahwa “Anarkisme ialah salah satu faham atau aliran dari sosialisme, oleh karenanya anarkisme itu adalah lawannya kapitalisme. Seorang anarkis, ialah pemeluk faham anarkisme itu, tidak suka dengan milik (eigendom), oleh karena hak milik itu lahirnya dari kapitalisme.
Istilah anarkis menunjuk pada setiap gerakan protes terhadap segala bentuk kemapanan, dalam bentuk kondisi ketiadaan otoritas tunggal dalam menentukan cara berpengetahuan, leaderless.
Feyerabend mengadopsi istilah anarkis dari salah satu aliran seni rupa dedaisme. Gagasan Feyerabend mengarah pada tuntutan untuk menumbuhkan iklim pluralistik dalam memperoleh pengetahuan.
Pluralisme teoritis dapat dipahami sebagai sebuah pandangan yang menolak standar tunggal dalam memperoleh pengetahuan. Pluralisme teoritis menolak klaim teori tertentu yang dalam stratifikasi kualitatif berbeda dan sebagai teori superior di atas inferioritas teori-teori lain dan dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan manusia yang valid.
Pemikiran Feyerabend sendiri dapat dikategorikan sebagai kritik terkait metode-metode dalam ilmu pengetahuan yang cenderung bercorak positivistik yang menurut Feyerabend terlalu kaku dan dinilai mengekang kebebasan berfikir para ilmuan.
Setidaknya penolakan Feyerabend atas kemapanan ilmu pengetahuan lahir dari kecurigaannya atas perkembangan ilmu pengetahuan yang sering mengarah pada pengkultusan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jika sudah demikian maka ilmu pengetahuan tidak jauh berbeda dengan ajaran-ajaran dogmatis dalam agama.
Akibatnya ilmu pengetahuan tidak jauh berbebda dengan ideologi yang akhirnya terpuruk seperti halnya agama yang menjadi sebuah dogma bagi para pengikutnya, sebagaimana pada ideologi tertentu katakanlah Marxisme maka bagi yang tidak sejalan dengan konsep Marxisme tidak dianggap sebagai bagian darinya.
Secara Singkat Filsafat anarkisme ini mengedepankan prinsip anti-otoritarianisme, kebebasan individu, dan solidaritas kolektif. Dengan demikian, epistemologi anarkisme tidak hanya bertumpu pada teori, tetapi juga praksis nyata di lapangan, termasuk dalam bentuk demonstrasi.
Demonstrasi sebagai Ruang Epistemik Anarkisme
Demonstrasi dapat dipandang sebagai “ruang epistemik” bagi kaum anarkis, di mana gagasan kritis terhadap negara, kapitalisme, maupun struktur sosial yang dianggap menindas diekspresikan secara terbuka. Perilaku demonstrasi dalam perspektif anarkisme tidak semata-mata bersifat destruktif, melainkan merupakan upaya untuk:
Pertama, Mendekonstruksi narasi hegemonik. Menantang klaim negara atau elit politik atas kebenaran tunggal.
Kedua, Membangun kesadaran kolektif melalui aksi massa, wacana tentang kebebasan dan perlawanan menjadi pengetahuan bersama.
Tiga, Melawan otoritas represif. Demonstrasi dijadikan instrumen perlawanan terhadap instrumen kekuasaan yang dianggap mengekang kebebasan individu dan rakyat.
Namun, dalam praktiknya, aksi anarko sering kali direduksi hanya pada aspek kekerasan dan perusakan. Pandangan semacam ini mengabaikan dimensi filosofis dan epistemologis anarkisme yang sesungguhnya kaya gagasan tentang etika kebebasan dan keadilan sosial.
Hal ini disebabkan karena adanya bias media. Media menjadi bias dalam mendeskripsikan kalangan anarko pada konteks wacana. Wacana yang dimunculkan terhadap kalangan anarko melalui deskripsi negatif bersumber pada pihak dominan, seperti pemerintah dan aparat negara. Dimana pihak-pihak tersebut memiliki kontrol dan kuasa atas sistem dan tatanan sosial masyarakat.
Sementara itu, media tidak sama sekali mendeskripsikan wacana kalangan anarko dari pihak anarko. Sehingga wacana media terhadap kalangan anarko menjadi kurang obyektif serta cenderung bias.
Kesan umum bahwa anarkhisme selalu identik dengan tindak kekerasan adalah sebuah pandangan yang parsial. Kekerasan sebagai media yang digunakan oleh gerakan anarkhis telah mendominasi pikiran masyarakat.
Seolah-olah, gerakan anarkhis selalu dan hanya meggunakan kekerasan seperti teror dan pemberontakan bersenjata. Padahal di sisi lain, tidak sedikit sayap anarkhis yang memilih penggunaan pendidikan kesadaran mengenai otonomi diri dan solidaritas antar manusia.
Representasi kalangan anarko didapati oleh beragam pihak berdasarkan hasil konstruksi realitas yang diciptakan oleh media. Penggambaran ini sesuai dengan konteks paham ideologi dominan baik dari media itu sendiri maupun pihak-pihak lain seperti masyarakat maupun pemerintah.
Maka dari itu, kalangan anarko pada akhirnya memilih untuk menggunakan cara-cara konvensional seperti menciptakan gangguan sebagai bentuk representasi kelompok mereka guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari pihak pemerintah.
Gangguan yang diciptakan oleh kalangan anarko sayangnya dikonstruksi oleh media, dengan mengubah pemaknaan sesungguhnya untuk menciptakan pemaknaan baru kepada masyarakat mengikuti sistem dan praktik hingga ideologi dari media tersebut.
Pemaknaan ini yang kemudian menyebar di masyarakat, dan digunakan dalam memandang kehadiran kalangan anarko beserta ideologi anarkisme yang mereka anut.
Kritik dan Tantangan
Meskipun anarkisme menawarkan epistemologi alternatif yang membebaskan, penerapannya dalam demonstrasi sering menghadapi tantangan. Negara cenderung menstigmatisasi anarko sebagai kriminal semata, sementara sebagian masyarakat tidak memahami landasan filosofisnya.
Tantangan lain adalah risiko terjebak dalam kontradiksi: perjuangan melawan dominasi justru bisa menimbulkan tindakan destruktif yang tidak produktif dalam jangka panjang.
Epistemologi filsafat anarkisme memandang pengetahuan sebagai hasil praksis kolektif dan pengalaman, bukan monopoli otoritas. Dalam konteks demonstrasi, anarkisme mengekspresikan dirinya melalui tindakan perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap menindas, sekaligus menciptakan ruang pengetahuan alternatif.
Namun, reduksi anarko semata-mata sebagai “perusuh” mengabaikan dimensi filosofis yang lebih dalam. Oleh karena itu, memahami anarko melalui epistemologi filsafat anarkisme memberi perspektif baru bahwa demonstrasi bukan hanya ruang konflik, melainkan juga ruang epistemik untuk membangun kesadaran kebebasan dan keadilan.
***
*) Oleh : Muhammad Alwi Hasan, S.hum., Pengurus lapeksdam NU Nganjuk.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |