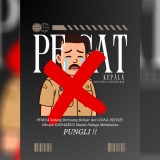TIMES JATIM, MALANG – Pemberantasan rokok ilegal di Indonesia saat ini tampak seperti upaya simbolis yang seakan dipentaskan, ketimbang aksi nyata yang menegaskan keberpihakan negara terhadap industri yang sah.
Direktorat Jenderal Bea Cukai secara rutin memamerkan angka penindakan ratusan juta batang rokok ilegal disita setiap tahun, seperti tercatat 285,8 juta batang dalam Januari–Mei 2025 (+32% dibanding tahun sebelumnya) meski jumlah penindakan justru turun.
Hasil besar ini tak serta merta mengartikan keberhasilan, karena data juga mengungkap bahwa cita-cita menekan peredaran rokok ilegal selalu kalah cepat dibanding laju pertumbuhannya. Indikator ini lebih menggarisbawahi bahwa akar persoalan belum tersentuh secara tuntas.
Memang, Bea Cukai meluncurkan berbagai operasi, mulai dari “Gempur Rokok Ilegal” hingga kolaborasi dengan instansi lokal dan TNI/Polri, serta merumuskan Satgas Pencegahan Rokok Ilegal. Namun efektivitasnya masih dipertanyakan karena tanpa pendekatan menyeluruh pada aspek hulu; produksi, distribusi, dan rantai ekonomi. Peningkatan operasi serupa hanya sekadar meredam gelombang sesaat.
Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus bahkan menyebut efisiensi Satgas terbentur oleh formulasi cukai yang belum menyentuh akar persoalan, di mana kenaikan tarif tinggi tanpa roadmap hanya mendorong konsumen turun ke produk lebih murah atau ilegal.
Ini diperkuat oleh kajian PPKE FEB UB yang memperingatkan kenaikan cukai mendorong peralihan konsumen ke rokok ilegal, dengan proporsi down‑trading yang mencapai 40% dari konsumen.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa penindakan di hilir tak akan maksimal jika kebijakan hulu justru membuka kesempatan bagi munculnya pasar gelap.
Lebih jauh lagi, struktur koordinasi antar lembaga masih rapuh. Meski Bea Cukai menyatakan sinergi dengan Satpol PP, TNI, Polri, dan jasa titipan rantai distribusi, dalam praktiknya, insiden keterlibatan oknum aparat justru memperlebar celah bagi pelaku ilegal.
Jika interpretasi interaksi lembaga masih bersifat restriktif dan gertakan formal semata, inisiatif akan berhenti di retorika. Di sisi lain, budaya internal aparat termasuk mentalitas "kami lawan mereka" sebagaimana banyak ditemui di Bea Cukai, bisa memicu kurangnya pendekatan edukatif, akuntabel, dan sistemik dalam menangani akar masalah atau memberi efek jera pada jaringan besar.
Fokus berlebihan pada penindakan lapangan pun melegitimasi kritik bahwa tindakan represif lebih menjadi “pamer operasi” ketimbang strategi jangka panjang. Data resmi memperlihatkan jumlah operasi menurun, tetapi volume barang beredar justru meningkat.
Ini sinyal kuat bahwa sistem pengawasan belum adaptif terhadap taktik distribusi ilegal seperti pengiriman lewat jasa titipan atau logistik modern, yang kini makin menjadi kanal utama penyelundupan.
Riset akademik menyimpulkan teknologi x-ray mobile dan sistem berbasis risiko di pelabuhan seperti Merak efektif, namun perlu diperluas dan diperkuat, termasuk melalui kontrol di jalur darat dan e-commerce.
Kecepatan transaksi digital juga harus direspons dengan penerapan digital compliance pada ritel tradisional dan mini market.
Aspek fiskal menjadi batu sandungan serius. Pajak tinggi memang menambah beban negara, tetapi bila terlalu eksesif tanpa skema transisi industri maupun sosial, kenaikan cukai hanya mendorong pergeseran konsumen ke produk murah atau ilegal.
Data menggambarkan bahwa kenaikan cukai hingga 50% dapat meningkatkan proporsi rokok ilegal dari 6,8% menjadi 11,6% dari keseluruhan pasar.
Rekomendasi PPKE dan GAPPRI menganjurkan moratorium kenaikan cukai hingga 2027, dengan kenaikan moderat maksimal 4–5% agar seimbang antara penerimaan negara dan kemampuan beli masyarakat. Tanpa kebijakan disiplin fiskal ini, strategi represif akan terus jadi upaya sisipan, bukan solusi utama.
Selain itu, edukasi publik yang gencar dinarasikan masih kurang menyentuh pemahaman kritis masyarakat. Sosialisasi lewat “Gempur Rokok Ilegal” memang dilakukan, tetapi belum sampai mengubah perilaku pedagang dan konsumen.
Studi menyebut pengetahuan masyarakat tentang ciri ilegal belum memadai dan upaya pelaporan warga belum optimal, meski Bea Cukai rutin menyosialisasikan. Komponen ini penting karena tanpa meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai watchdog lokal, distribusi ilegal akan terus menyebar di level paling bawah.
Tak kalah penting, pembersihan internal aparat harus jadi prioritas serius. Komitmen transparansi tentang kasus oknum aparat yang terlibat perlu dipublikasikan secara terbuka. Sebab, kepercayaan publik memudar saat aparat yang mestinya jadi penegak hukum malah menjadi pelindung jaringan ilegal yang terorganisir.
Reformasi institusi ini juga harus merambah ke pola pelatihan budayanya, mengubah mindset yang saling mencurigai masyarakat menjadi kolaboratif dan akuntabel.
Pemberantasan rokok ilegal harus bukan agenda tersier. Jika dipandang sebagai isu sampingan, jual moderat dan habis tinta, maka hasilnya hanya simulasi kesuksesan operasional.
Padahal persoalan ini menyentuh tiga elemen penting: kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan industri tembakau yang legal dan menyerap puluhan juta tenaga kerja.
Tanpa sinergi kebijakan fiskal yang berimbang, teknologi pengawasan mutakhir, budaya internal aparat yang inklusif, serta peran aktif masyarakat, maka setiap angka sitaan hanya akan menjadi catatan operasi, bukan prestasi sistemik.
Indonesia butuh strategi holistik dari hulu ke hilir, dari kebijakan ke implementasi bukan sekadar gempuran temporer yang lebih menonjolkan foto bersama petugas ketimbang perbaikan struktural.
Dengan refleksi seperti ini, harapan terbesar bukan sekadar menurunkan jumlah batang rokok ilegal di jalanan, melainkan membangun sistem yang teguh, menciptakan efek jera, dan mewujudkan industri tembakau yang sehat, mandiri, dan terkontrol sesuai aturan negara.
Negeri ini membutuhkan skema yang tidak hanya “gempur”, tetapi menghancurkan ekosistem pelanggaran dari akarnya.
***
*) Oleh : Thaifur Rasyid, Pengurus Komunitas Kretek Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |