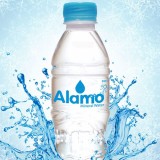TIMES JATIM, MALANG – Di era hiperdigital, media bukan sekadar penyampai berita, melainkan juga pembentuk persepsi kolektif, arsitek moral publik, dan kadang tanpa disadari penggali jurang antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kultural.
Arus informasi yang deras, kompetisi rating, dan obsesi terhadap “engagement” membuat batas antara jurnalisme dan hiburan semakin kabur. Namun, ketika kamera diarahkan ke ruang-ruang sakral seperti pesantren.
Pertanyaan mendasar kembali menggema: apakah kebebasan media memberi hak untuk menafsir ulang tradisi keagamaan dengan lensa sensasional? Ataukah ada batas moral yang harus dijaga agar kebebasan tidak menjelma menjadi pelecehan?
Kasus viral yang melibatkan tayangan Xpose Uncensored di Trans7, yang menampilkan Pondok Pesantren Lirboyo dalam narasi yang dinilai merendahkan, menjadi cermin betapa rapuhnya keseimbangan antara ekspresi kreatif dan tanggung jawab etik.
Dalam tayangan tersebut, potongan narasi dan visual dianggap menyinggung kehormatan kiai dan kehidupan santri mulai dari cara mereka beraktivitas hingga praktik keseharian yang dimaknai secara salah. Reaksi publik pun meledak: seruan #BoikotTrans7 menggema di jagat maya, LBH Ansor turun tangan, dan masyarakat pesantren menuntut klarifikasi.
Di balik hiruk-pikuk itu, persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar “salah tayang” atau “framing media.” Ini tentang krisis epistemik dalam dunia media digital ketika nilai dijadikan komoditas, dan kehormatan sosial ditukar dengan klik serta rating.
Media, Etika, dan Krisis Representasi
Dalam lanskap digital yang ditopang algoritma, kebenaran sering kali dikalahkan oleh sensasi. Teori Attention Economy (Herbert Simon, 1971) menjelaskan bahwa di era banjir informasi, perhatian menjadi mata uang paling berharga.
Semakin sensasional sebuah tayangan, semakin besar peluangnya untuk viral. Tapi di balik logika ini tersembunyi bahaya: eksploitasi simbol keagamaan dan budaya demi kepentingan komersial.
Kasus Trans7 memperlihatkan betapa rentannya ruang sakral seperti pesantren saat ditempatkan di bawah sorotan kamera yang mengedepankan dramatika visual.
Pesantren yang sejatinya merupakan locus pendidikan moral dan spiritual disederhanakan menjadi potongan visual yang lucu, asing, atau bahkan eksotis di mata audiens urban. Padahal, di balik kesederhanaan itu, tersimpan warisan intelektual dan spiritual yang membentuk karakter bangsa.
Sebagaimana diingatkan oleh Clifford Geertz dalam kajiannya tentang Islam Jawa, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan “mikrokosmos moralitas” yang menjaga kesinambungan nilai.
Ketika ruang itu diperlakukan sebagai tontonan tanpa penghormatan, yang terjadi bukanlah edukasi publik, melainkan banalitas religius agama yang dijadikan bahan hiburan.
Reaksi keras masyarakat Lirboyo sesungguhnya mencerminkan perlawanan terhadap dominasi narasi media. Spiral of Silence (Noelle-Neumann, 1974) menjelaskan bahwa opini mayoritas yang menguasai ruang publik dapat membungkam kelompok yang tidak sejalan.
Dalam konteks ini, framing negatif terhadap pesantren berpotensi memperkuat stereotip lama bahwa dunia santri adalah dunia tertinggal, kolot, dan tidak relevan dengan modernitas.
Kebisuan kelompok pesantren selama ini, yang lebih memilih diam ketika disalahpahami, membuat ruang wacana dikuasai oleh pihak luar yang tak memahami tradisi internalnya.
Maka ketika Trans7 menayangkan narasi yang dianggap melecehkan, reaksi keras itu bukan sekadar soal marah; ia adalah bentuk reclaiming terhadap narasi yang selama ini dirampas.
Antara Kamera dan Kesakralan
Dalam perspektif etika Islam, kehormatan (‘ird) adalah sesuatu yang suci. Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini,” (HR. Bukhari dan Muslim).
Ayat dan hadis semacam ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan seseorang terlebih seorang ulama bukan hanya adab, tetapi juga ibadah. Maka ketika media menyajikan tayangan yang menyinggung kehormatan para kiai, dampaknya tidak berhenti pada level sosial, melainkan juga spiritual.
Dalam Islam, ada prinsip tatsabbut (verifikasi) sebagaimana dalam QS. al-Hujurat 49:6 “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."
Ayat ini adalah fondasi etik bagi jurnalisme Islam: klarifikasi sebelum publikasi. Tapi di era digital, prinsip tatsabbut sering dikorbankan atas nama kecepatan dan eksklusivitas.
Trans7 mungkin tidak bermaksud menista, tetapi niat baik tidak membatalkan dampak buruk. Sebab, seperti kata Imam al-Ghazali, “Bukan hanya yang berbicara yang berdosa, tetapi juga yang menyebarkan kebodohan tanpa ilmu.”
Kebebasan pers adalah pilar demokrasi, tetapi ia tidak absolut. Pasal 28J UUD 1945 jelas menyatakan bahwa kebebasan harus disertai tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
Maka, kasus ini menantang kita untuk menimbang kembali: apakah media hanya tunduk pada algoritma pasar, atau juga pada etika sosial yang melindungi martabat komunitas?
Trans7 bukan sekadar lembaga penyiaran; ia adalah institusi yang membentuk imajinasi publik. Dalam Teori Mediatization (Hjarvard, 2008), media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga menciptakannya.
Tayangan seperti “Xpose Uncensored” tidak berdiri netral: ia membentuk cara masyarakat memandang dunia pesantren. Jika framing-nya keliru, dampaknya bisa sistemik menciptakan jarak antara masyarakat urban dan kultur santri, antara modernitas dan moralitas.
Sosial dan Spiritualitas Publik
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk merefleksikan hubungan antara media dan agama di Indonesia. Pesantren bukan entitas tertutup. Ia adalah simpul kebudayaan yang telah melahirkan ulama, pejuang, dan intelektual bangsa.
Tapi ketika dunia pesantren dihadirkan tanpa konteks, hanya melalui potongan visual yang mengundang tawa, yang hilang bukan sekadar makna, melainkan juga martabat.
Kita hidup di zaman ketika kamera bisa menjadi cermin sekaligus pisau. Ia bisa merekam keindahan, tetapi juga bisa memotong makna. Di sinilah pentingnya media literacy berbasis nilai: publik harus belajar menonton dengan kesadaran, bukan sekadar konsumsi. Dan media harus belajar menyiarkan dengan adab, bukan sekadar kecepatan.
Seorang kiai Lirboyo pernah berkata, “Santri bukan orang yang anti-kritik, tetapi orang yang diajari adab sebelum ilmu.” Barangkali kalimat itu perlu kita balikkan pada media: jurnalis bukan orang yang anti-viral, tetapi orang yang seharusnya beradab sebelum siar.
Kasus Trans7 dan Lirboyo bukan sekadar benturan antara televisi dan pesantren, tetapi antara dua paradigma: antara logika algoritma dan logika adab. Satu berpijak pada engagement, satu berpijak pada kehormatan. Keduanya bisa bertemu jika kita mau menata ulang etika komunikasi publik di negeri yang berakar pada nilai-nilai religius ini.
Maka, pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah, tetapi bagaimana agar media dan masyarakat bisa saling belajar. Media belajar menghormati ruang sakral, sementara pesantren belajar mengartikulasikan dirinya di ruang publik modern. Hanya dengan begitu, kebebasan dan kehormatan tidak lagi berhadap-hadapan, melainkan berjalan berdampingan.
Sebab, sebagaimana diingatkan dalam QS. An-Nur 24:19, “Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya aib di antara orang beriman, bagi mereka azab yang pedih.”
Dan di situlah makna terdalam dari tanggung jawab media: bukan hanya menyampaikan berita, tetapi menjaga kemanusiaan di dalamnya.
***
*) Oleh : Thaifur Rasyid, S.H., M.H., Praktisi Hukum.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |