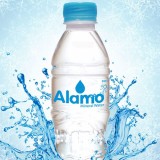TIMES JATIM, MALANG – Kepercayaan publik adalah fondasi paling mendasar bagi tegaknya negara. Tanpa kepercayaan, aturan kehilangan wibawanya, program kehilangan legitimasi, dan janji-janji pembangunan hanya menjadi gema di ruang hampa.
Sayangnya, di Indonesia hari ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah kian rapuh. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpastian dalam pengelolaan pajak dan kekayaan negara.
Pajak, dalam teori klasik, adalah kontribusi rakyat untuk membiayai negara. Ia adalah bentuk gotong royong modern, di mana setiap warga menyisihkan sebagian hartanya demi kepentingan bersama. Namun, realitas yang kita lihat sering jauh dari ideal.
Berulang kali kita disuguhi kasus korupsi pajak, mulai dari manipulasi hingga permainan di meja birokrasi. Rakyat diminta taat membayar, tetapi di sisi lain, uang itu justru bocor ke kantong segelintir pejabat. Ironi ini membuat rakyat bertanya: untuk siapa sebenarnya pajak ini dikumpulkan?
Lebih parah lagi, ketidakpastian penggunaan pajak diperparah oleh minimnya transparansi. Anggaran belanja negara kerap hanya dipahami sebagai angka-angka besar yang sulit dijangkau nalar publik.
Padahal, dalam negara demokrasi, setiap rupiah yang keluar seharusnya bisa dilacak, dipertanggungjawabkan, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tetapi yang sering muncul adalah berita megakorupsi, fasilitas mewah pejabat, serta gaya hidup yang jauh dari realitas mayoritas masyarakat.
Di sisi lain, kekayaan negara yang melimpah sumber daya alam, pajak, hingga dividen BUMN seakan tidak pernah sepenuhnya kembali pada rakyat. Minyak, batu bara, nikel, hingga hasil hutan yang seharusnya menopang kesejahteraan, justru banyak dikuasai oleh oligarki dan investor besar.
Negara tampak hadir hanya sebagai regulator yang kadang goyah oleh tekanan kepentingan. Akibatnya, rakyat yang sebenarnya pemilik sah kekayaan alam hanya menjadi penonton yang menanggung dampak eksploitasi: kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan harga kebutuhan yang terus melonjak.
Di tengah kondisi itu, publik semakin skeptis. Bagaimana bisa diminta taat pada pajak jika mereka yang mengelola pajak justru menyelewengkannya? Bagaimana bisa percaya pada janji kesejahteraan jika kekayaan negara lebih banyak dinikmati segelintir elit? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema di ruang publik, menciptakan jurang kepercayaan antara pemerintah dan rakyat.
Kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan retorika belaka. Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika pajak benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik, maka rakyat dengan sendirinya akan lebih rela membayar.
Sebaliknya, jika pajak hanya menjadi sumber berita korupsi, maka resistensi akan terus tumbuh, baik secara diam-diam melalui penghindaran pajak, maupun secara terbuka lewat gelombang protes.
Sejarah menunjukkan bahwa retaknya kepercayaan pada pengelolaan pajak bisa berujung pada krisis besar. Lihat bagaimana Revolusi Perancis meletus, salah satunya karena rakyat muak pada sistem pajak yang timpang.
Kaum elit hidup berfoya-foya sementara rakyat menanggung beban. Narasi serupa, meski dalam konteks berbeda, juga bisa muncul di Indonesia jika pemerintah tidak serius memperbaiki tata kelola.
Namun, kritik ini tidak berhenti pada kecaman. Ada peluang sekaligus tanggung jawab besar untuk memperbaiki keadaan. Transparansi pajak harus menjadi prioritas. Pemerintah bisa membangun sistem digital yang memungkinkan rakyat melacak kemana uang mereka digunakan.
Laporan penggunaan pajak harus disajikan dengan bahasa sederhana, bukan sekadar tabel rumit. Publik berhak tahu, misalnya, berapa pajak yang dipakai membangun sekolah di desanya, atau berapa yang masuk untuk subsidi kesehatan.
Selain itu, pemberantasan korupsi pajak harus dilakukan dengan keberanian politik yang nyata. Tidak cukup hanya menindak pegawai kelas bawah, sementara pejabat tinggi atau mafia pajak lolos dari jerat hukum.
Rakyat menilai bukan dari pidato, melainkan dari konsistensi penegakan hukum. Jika kasus besar bisa dibongkar, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa negara benar-benar berpihak pada rakyat.
Di sisi pengelolaan kekayaan negara, paradigma juga harus diubah. Sumber daya alam tidak bisa selamanya dijadikan komoditas untuk segelintir perusahaan. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa kekayaan itu benar-benar menetes pada rakyat dalam bentuk harga terjangkau, lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Otonomi daerah juga harus diberdayakan agar kekayaan lokal tidak selalu tersedot ke pusat tanpa imbal balik yang sepadan.
Kepercayaan publik tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari akumulasi pengalaman: apakah rakyat merasa diperlakukan adil, apakah suara mereka didengar, apakah uang mereka benar-benar kembali pada kesejahteraan. Jika pemerintah hanya sibuk menampilkan pencitraan tanpa menyentuh akar persoalan, maka jurang ketidakpercayaan akan semakin lebar.
Kita tidak sedang bicara soal angka defisit atau surplus semata. Kita sedang bicara soal legitimasi sebuah negara. Sebab, negara tanpa kepercayaan publik ibarat rumah megah tanpa pondasi: tampak kokoh di luar, tetapi rapuh dan siap runtuh kapan saja.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyadari bahwa setiap rupiah pajak yang dikorupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan yang nilainya jauh lebih mahal. Dan sekali kepercayaan hilang, membangunnya kembali akan lebih sulit daripada sekadar menutup defisit anggaran.
Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh seberapa serius pemerintah menjaga kepercayaan rakyatnya. Bukan lewat janji, bukan lewat jargon, tetapi lewat keberanian untuk jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan bersama. Sebab, negara ini sejatinya berdiri bukan di atas kekayaan alam semata, tetapi di atas kepercayaan rakyat yang memilih untuk percaya.
***
*) Oleh : Moh. Farhan Aziz, S.AP., Anggota Bidang 2 PC PMII Kota Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |