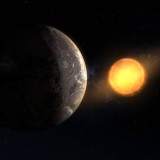TIMES JATIM, MALANG – Pemerintah baru saja mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai hampir Rp16,23 triliun untuk kuartal akhir 2025 hingga 2026. Isinya mencakup bantuan pangan, program padat karya, subsidi bagi kelompok rentan, hingga insentif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sekilas, kebijakan ini terdengar manis: negara hadir memberi solusi atas masalah kemiskinan, ketimpangan, dan kelesuan ekonomi global. Namun, apakah stimulus ini benar-benar akan mengangkat martabat rumah tangga miskin, ataukah hanya menjadi penenang sesaat yang meredam gejolak tanpa menyentuh akar masalah?
Kebijakan stimulus memang bukan hal baru dalam manajemen ekonomi. Banyak negara menggunakannya saat terjadi krisis, baik karena pandemi, resesi, maupun lonjakan harga global. Di Indonesia, stimulus sosial kerap menjadi instrumen politik populis yang digadang-gadang mampu menjaga daya beli masyarakat bawah.
Padahal, jika dicermati, pola yang berulang menunjukkan bahwa bantuan sosial sering kali tidak lebih dari “perban sementara” untuk luka kronis yang tak pernah diobati secara tuntas. Angka kemiskinan memang bisa turun secara statistik, tetapi kualitas hidup warga miskin tetap stagnan, bahkan rentan kembali terperosok.
Salah satu masalah klasik dari paket stimulus adalah efektivitas distribusi. Sejarah mencatat betapa banyaknya bantuan yang salah sasaran, bocor di tengah jalan, atau dimonopoli oleh elite lokal.
Program bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada dekade sebelumnya menjadi contoh gamblang: beras berkualitas rendah, jumlah yang tidak sesuai, hingga warga yang seharusnya berhak justru tak kebagian.
Kini, saat pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah untuk subsidi pangan dan bantuan tunai, apakah mekanisme pengawasan sudah lebih transparan? Ataukah pola lama akan kembali terulang dengan wajah baru?
Di sisi lain, stimulus ekonomi sering kali berhenti di level konsumsi, bukan produksi. Bantuan pangan memang mengisi perut, tetapi tidak mengubah nasib petani yang justru tersisih oleh impor. Program padat karya memberi penghasilan sementara, tetapi tanpa akses berkelanjutan terhadap lapangan kerja formal yang layak.
Subsidi UMKM memang meringankan beban, tetapi tidak otomatis membuat usaha kecil bisa bersaing di pasar yang dikuasai korporasi besar. Dengan kata lain, stimulus bisa memberi oksigen jangka pendek, tetapi tidak menjamin keberlangsungan hidup yang sehat di masa depan.
Yang lebih memprihatinkan, stimulus sosial kerap dikemas dalam narasi “kebaikan negara” yang seolah datang dari kemurahan hati pemerintah, bukan dari hak rakyat atas anggaran publik. Padahal, dana Rp16,23 triliun itu bukan hadiah dari penguasa, melainkan uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak, sumber daya alam, dan utang negara.
Ketika stimulus diposisikan sebagai “bantuan belas kasihan,” maka terjadi reduksi makna: rakyat dipandang sebagai penerima, bukan sebagai pemilik sah dari hak-hak ekonomi mereka. Inilah bentuk subtil dari politik patronase yang memperkuat ketergantungan rakyat pada negara, alih-alih membangun kemandirian mereka.
Tentu kita tidak bisa menafikan pentingnya subsidi sosial, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Harga pangan dunia berfluktuasi, ancaman perubahan iklim mengganggu produksi, dan tensi geopolitik membuat biaya impor melonjak.
Rumah tangga miskin adalah kelompok paling rentan menghadapi guncangan ini. Namun, alih-alih hanya mengandalkan subsidi, pemerintah seharusnya berani menggeser paradigma kebijakan: dari sekadar menyalurkan bantuan, menuju pemberdayaan yang berkelanjutan.
Program pendidikan, pelatihan keterampilan, akses permodalan yang adil, serta perlindungan petani dan nelayan jauh lebih strategis untuk membangun fondasi ekonomi rakyat.
Kritik lain yang tak kalah penting adalah soal keterbukaan informasi dan evaluasi kebijakan. Stimulus sebesar Rp16,23 triliun bukan angka kecil, dan publik berhak tahu bagaimana detail penggunaannya, siapa yang mengawasi, serta apa indikator keberhasilannya.
Selama ini, laporan tentang efektivitas bantuan sosial sering kali kabur, lebih banyak berupa klaim politik ketimbang data empiris yang bisa diverifikasi. Tanpa transparansi, stimulus hanya akan menjadi ruang baru bagi praktik korupsi yang kian sulit diberantas.
Stimulus ekonomi juga perlu dilihat dalam kerangka besar tata kelola negara. Jika pada saat yang sama pemerintah tetap membuka kran impor pangan besar-besaran, mengorbankan petani lokal, dan memberi karpet merah pada investasi ekstraktif, maka stimulus sosial hanyalah kompensasi kecil atas kerugian struktural yang diciptakan oleh kebijakan makro. Dengan demikian, paket bantuan ini tampak seperti “memberi dengan tangan kanan, tetapi mengambil lebih banyak dengan tangan kiri.”
Stimulus ekonomi harus dipahami bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga cermin dari orientasi politik negara. Apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat miskin, atau hanya berusaha menjaga stabilitas sosial demi kelanggengan kekuasaan? Pertanyaan ini menuntut jawaban jujur. Sebab, jika stimulus hanya menjadi penenang sesaat, kita sedang membangun ilusi kesejahteraan di atas fondasi rapuh.
Negara seharusnya hadir bukan untuk menghibur rakyat dengan subsidi, melainkan untuk mengubah struktur ekonomi agar rakyat tidak lagi bergantung pada belas kasihan, melainkan berdiri tegak dengan martabatnya sendiri.
***
*) Oleh : Iswan Tunggal Nogroho, Praktisi Pendidikan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |