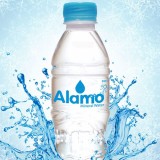TIMES JATIM, MALANG – Fenomena meningkatnya laporan polisi yang diajukan orang tua terhadap guru dan kiai atas tindakan disiplin fisik mencerminkan pergeseran paradigma mendasar dalam dunia pendidikan kita. Baru-baru ini di Kabupaten Malang, ada seorang kiai yang dilaporkan oleh wali santri ke polisi karena mendisiplinkan santri dengan cara memukul memakai rotan, hingga sang Kiai menjadi tersangka.
Apa yang dahulu dianggap sebagai bagian alamiah dari proses pembelajaran kini berhadapan dengan kerangka hukum modern yang menekankan perlindungan hak anak.
Paradoks ini memunculkan pertanyaan mendasar, bagaimana hukum Indonesia mengakomodasi tradisi pendidikan yang telah mengakar dengan prinsip-prinsip perlindungan anak universal? Sehingga berbagai peristiwa pelaporan ini menjadi konflik Nilai dalam ruang pendidikan kita.
Dalam kesempatan kali ini kita akan memgurai bahwa konflik antara otoritas tradisional guru dengan perlindungan hukum anak bukanlah sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan refleksi dari transformasi sosial yang lebih luas dalam masyarakat Indonesia.
Melalui analisis multidimensi yang menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan antropologi budaya, tulisan ini akan mengeksplorasi kompleksitas isu ini dan mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi kebutuhan disiplin pendidikan dengan jaminan perlindungan hak anak.
Kewenangan Edukatif dan Perlindungan Anak
Landasan Konstitusional dan Regulasi Perlindungan Anak. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
Mandat konstitusional ini kemudian dielaborasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014.
Pasal 54 UU Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya."
Ketentuan ini tidak memberikan pengecualian untuk tindakan disiplin edukatif, yang menciptakan ambiguitas dalam praktik pendidikan.
Lebih lanjut, Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Sementara Pasal 80 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut.
Meskipun pasal ini secara spesifik mengatur kekerasan seksual, namun dalam praktik penegakan hukum, interpretasi "kekerasan" sering diperluas mencakup tindakan fisik apa pun yang dilakukan terhadap anak.
Ambiguitas Hukum dalam Konteks Pendidikan
Paradoks muncul ketika menganalisis UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kewenangan kepada pendidik untuk melakukan pembinaan peserta didik. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan."
Istilah "pembimbingan dan pelatihan" dalam konteks tradisi pendidikan Indonesia secara historis mencakup aspek tindakan disiplin. Namun, UU Sisdiknas tidak secara eksplisit mendefinisikan batasan-batasan pembimbingan ini, khususnya dalam kaitannya dengan tindakan fisik sebagai instrumen disiplin.
Ambiguitas ini diperparah oleh Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menekankan kompetensi profesional dan pedagogik guru, namun tidak memberikan panduan yang jelas mengenai metode disiplin yang diperbolehkan dalam konteks perlindungan anak.
Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Hak-Hak Anak terikat pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi tersebut. Prinsip ini mengharuskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.
Namun, interpretasi "kepentingan terbaik" dalam konteks pendidikan menjadi kompleks. Apakah kepentingan terbaik anak adalah perlindungan mutlak dari segala bentuk tindakan fisik, ataukah pembentukan karakter dan disiplin yang mungkin memerlukan tindakan korektif? Hukum Indonesia belum memberikan jawaban definitif atas pertanyaan mendasar ini.
Dari Otoritas Tradisional ke Hak Individual
Genealogi Otoritas Guru dalam Tradisi Jawa. Untuk memahami kompleksitas isu ini, penting untuk menganalisis konteks historis otoritas guru dalam tradisi budaya Indonesia, khususnya Jawa.
Konsep "guru" dalam filosofi Jawa tidak hanya merujuk pada profesi, tetapi pada posisi sakral yang dirangkum dalam ungkapan "guru, ratu, wong tua" - tiga figur otoritas yang harus dihormati dan dipatuhi tanpa syarat.
Dalam konteks pesantren, otoritas kiai bahkan lebih kompleks lagi. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual, otoritas moral, dan pemimpin masyarakat.
Tradisi "ta'dhim al-ustadz" (menghormati guru) dalam budaya pesantren menempatkan kiai pada posisi yang hampir tidak dapat dikritik atau dipertanyakan apalagi oleh para santrinya.
Analisis historis menunjukkan bahwa hukuman fisik dalam konteks pendidikan tradisional bukan dipandang sebagai kekerasan, melainkan sebagai manifestasi kepedulian dan bagian integral dari proses pembentukan karakter. Konsep "keras tetapi sayang" telah mengakar dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia selama berabad-abad.
Namun demikian, dibeberapa tahun terakhir ini, tradisi itu hilang dan bahkan mengalami pergeseran paradigma, dari kolektif ke Individual.
Transformasi sosial Indonesia dalam era reformasi telah menghasilkan pergeseran mendasar dari nilai-nilai kolektivis tradisional menuju penekanan pada hak individual dan kesadaran hak asasi manusia. Generasi orang tua milenial yang lebih familiar dengan diskursus hak asasi manusia dan perlindungan anak tidak lagi secara otomatis menerima metode disiplin tradisional.
Media sosial dan akses informasi global telah mempercepat transformasi ini. Orang tua kini memiliki paparan terhadap berbagai pendekatan disiplin alternatif dan lebih sadar terhadap dampak psikologis potensial dari hukuman fisik. Hal ini menciptakan kesenjangan budaya antara generasi yang berbeda dalam memandang ukuran disiplin yang dapat diterima.
Berbagai perubahan jaman diera modern ini juga berkontribusi atas pergeseran tersebut, dari individualisasi dan hingga Erosi Otoritas Tradisional.
Proses individualisasi dalam masyarakat Indonesia modern juga berkontribusi pada erosi struktur otoritas tradisional. Orang tua tidak lagi secara otomatis menghormati otoritas guru atau kiai, tetapi cenderung mempertanyakan dan mengevaluasi tindakan mereka berdasarkan standar individual mereka sendiri.
Fenomena ini diperkuat oleh pemberdayaan ekonomi dan kemajuan pendidikan orang tua yang menciptakan kepercayaan diri untuk menantang otoritas tradisional. Dalam banyak kasus, orang tua merasa memiliki latar belakang pendidikan dan status sosial yang setara atau bahkan superior dibanding guru, sehingga mereka tidak merasa berkewajiban untuk menerima tindakan guru tanpa pertanyaan bahkan cenderung tidak menghormati otoritas guru sebagai pengajar dan pendidik.
Benturan Kerangka Hukum
Dalam sistem hukum common law, terdapat doktrin in loco parentis yang memberikan kewenangan kepada institusi pendidikan untuk bertindak "menggantikan orang tua" dalam mengatur dan mendisiplinkan siswa.
Meskipun Indonesia menganut sistem hukum sipil, konsep serupa dapat ditemukan dalam tradisi hukum adat dan praktik pendidikan tradisional, khususnya dipesantren salaf.
Namun, implementasi doktrin ini dalam konteks hukum Indonesia modern menghadapi beberapa tantangan. Pertama, tidak adanya pengakuan legislatif eksplisit terhadap konsep in loco parentis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Kedua, konflik potensial dengan prinsip otoritas orang tua yang diakui dalam hukum keluarga Indonesia.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mengatur dan mendidik anak. Ketika guru atau kiai melakukan tindakan disiplin fisik tanpa persetujuan eksplisit dari orang tua, dapat terjadi konflik yurisdiksi antara otoritas orang tua dengan otoritas pendidikan yang dilakukan oleh guru atau kiai dipesantren.
Dari perspektif hukum hak asasi manusia, setiap pembatasan hak (termasuk dalam konteks pendidikan) harus memenuhi uji proporsionalitas. Uji ini meliputi (1) tujuan yang sah, (2) kesesuaian, (3) kebutuhan, dan (4) proporsionalitas dalam arti sempit.
Dalam konteks tindakan disiplin edukatif, tujuan yang sah dapat berupa pembentukan karakter, koreksi perilaku, atau menjaga ketertiban dalam lingkungan pendidikan. Namun, kesesuaian dan kebutuhan hukuman fisik sebagai metode disiplin menjadi dipertanyakan ketika metode alternatif non-fisik tersedia dan berpotensi lebih efektif.
Proporsionalitas dalam arti sempit mengharuskan bahwa tingkat keparahan tindakan disiplin tidak boleh berlebihan dibanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Standar ini bersifat subjektif dan kontekstual, yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik pendidikan.
Dalam menghadapi fenomena pelaporan guru yang marak pada akhir-akhir ini, perlu dilihat dengan pendekatan hukum pidana dan hukum administrasi.
Fenomena pelaporan guru ke polisi mencerminkan kecenderungan untuk menggunakan pendekatan hukum pidana dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini bermasalah karena hukum pidana bersifat menghukum dan tidak selalu mengatasi keprihatinan pendidikan yang mendasar.
Pendekatan alternatif melalui mekanisme hukum administrasi, seperti proses disiplin profesional atau mediasi melalui otoritas pendidikan, berpotensi lebih tepat dan konstruktif. Namun, tidak adanya kerangka hukum administrasi yang komprehensif untuk sengketa yang berkaitan dengan pendidikan mendorong para pihak untuk menggunakan upaya hukum pidana.
Sehingga pendekatan yang cenderung memakai hukum pidana ini akan berdampak Psiko-Sosial, dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dimana pendekatan hukum pidana ini berefek Menakutkan pada Otoritas Edukatif.
Kriminalisasi tindakan disiplin telah menciptakan efek menakutkan di kalangan pendidik. Banyak guru dan kiai menjadi enggan untuk melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk mempertahankan standar pendidikan dan disiplin kelas karena takut akan konsekuensi hukum (Dipenjara).
Akibatnya, menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang berlebihan tanpa panduan yang jelas dapat menghasilkan lingkungan pendidikan yang permisif dan kontraproduktif untuk pembentukan karakter dan pencapaian akademik. Ketika guru tidak dapat secara efektif menjaga disiplin, kualitas pembelajaran secara keseluruhan dapat menurun.
Dampak yang lain adalah bahaya Moral dan perilaku siswa, kesadaran siswa terhadap perlindungan hukum yang mereka miliki dapat menciptakan bahaya moral di mana siswa memanfaatkan kerangka hukum untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Fenomena "siswa melaporkan guru" dapat menghasilkan ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak sehat dalam hubungan guru-siswa.
Hal ini khususnya bermasalah dalam konteks pesantren di mana hirarki tradisional dan penghormatan terhadap otoritas merupakan nilai-nilai mendasar yang ingin ditanamkan. Erosi hirarki ini dapat mengancam esensi sistem pendidikan pesantren itu sendiri.
Kemudian, dampak pada hubungan Guru-Siswa juga akan bermasalah. Kriminalisasi disiplin fisik dapat menghasilkan perubahan mendasar dalam sifat hubungan guru-siswa. Hubungan yang secara tradisional berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kasih sayang orang tua berpotensi menjadi legalistik dan transaksional.
Studi psikologis menunjukkan bahwa hubungan berbasis ketakutan (dalam hal ini, takut akan konsekuensi hukum) tidak kondusif untuk pembelajaran yang efektif dan pengembangan karakter. Siswa mungkin kehilangan rasa hormat terhadap guru yang dianggap "tidak berdaya" atau "takut," yang dapat melemahkan efektivitas pendidikan.
Menuju Solusi Komprehensif
Menghadapi fenomena ini, kita memerlukan reformasi legislatif yang komprehensif yang memberikan panduan yang jelas mengenai batasan disiplin pendidikan. Reformasi ini harus mengakomodasi beberapa elemen kunci.
Pertama, pengakuan eksplisit otoritas pendidikan dalam kerangka hukum positif Indonesia, dengan delineasi kekuasaan dan batasan yang jelas.
Kedua, pembentukan perlindungan prosedural untuk tindakan disiplin, termasuk keterlibatan orang tua, persyaratan dokumentasi, dan mekanisme banding.
Ketiga, penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang dirancang khusus untuk konflik yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga tidak melulu menggunakan pendekatan hukum pidana.
Selain pendekatan hukum pidana yang selama ini digunakan dalam penyelesaian konflik dalam pendidikan, ada beberapa pendekatan yang mungkin lebih cocok digunakan dalam penyelesaian konflik dalam pendidikan diantaranya adalah pendekatan Keadilan Restoratif.
Indonesia dapat mengadopsi model keadilan restoratif dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan pendidikan. Model ini menekankan pada perbaikan hubungan, saling pengertian, dan pemecahan masalah kolaboratif daripada hukuman.
Keadilan restoratif khususnya tepat dalam konteks pendidikan karena fokus pada pembelajaran, pertumbuhan, dan pembangunan masyarakat. Model ini dapat mengakomodasi nilai-nilai tradisional pengampunan dan harmoni masyarakat sambil mengatasi keprihatinan modern tentang perlindungan anak.
Disisi lain diperlukan juga pengembangan profesional dan Pelatihan bagi guru yang lebih mendalam dalam penanganan pendisiplinan murid. Hal ini untuk menghadirkan solusi komprehensif yang memerlukan investasi dalam pengembangan profesional untuk pendidik. Program pelatihan harus mencakup modul tentang psikologi anak, metode disiplin alternatif, kesadaran hukum, dan keterampilan resolusi konflik.
Sertifikasi profesional dan persyaratan pendidikan berkelanjutan dapat memastikan bahwa pendidik dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi situasi disiplin yang kompleks secara efektif dan legal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan tindakan disiplin yang tidak tepat sambil mempertahankan efektivitas pendidikan.
Menjembatani Nilai Tradisional dan Hak Modern
Pendekatan dialogis diperlukan dalam pembuatan kebijakan, pengembangan kebijakan dalam area budaya yang sensitif memerlukan pendekatan dialogis yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemimpin tradisional, pendidik, orang tua, ahli hukum, dan advokat hak anak. Indonesia perlu membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk memfasilitasi dialog berkelanjutan dan pembangunan konsensus.
Mediasi budaya dapat membantu mengidentifikasi titik temu antara nilai-nilai yang tampaknya bertentangan dan mengembangkan solusi yang sensitif budaya yang menghormati tradisi sambil menjunjung tinggi standar hak asasi manusia modern.
Mengingat sifat komunal masyarakat Indonesia, solusi berbasis komunitas mungkin lebih efektif daripada pendekatan regulatif dari atas ke bawah. Mekanisme tradisional seperti musyawarah mufakat dapat diadaptasi untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pendidikan di tingkat komunitas.
Keterlibatan komunitas dalam mengembangkan panduan lokal untuk disiplin pendidikan dapat meningkatkan penerimaan dan kepatuhan sambil memastikan kesesuaian budaya dari solusi tersebut.
Dari paparan diatas bahwa fenomena meningkatnya laporan polisi terhadap guru dan kiai atas tindakan disiplin mencerminkan ketegangan mendasar antara nilai-nilai pendidikan tradisional dan kerangka hak asasi manusia modern dalam masyarakat Indonesia.
Konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan formalistik hukum semata, tetapi memerlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan reformasi hukum, mediasi budaya, dan pengembangan profesional.
Menghadapi fenomena ini dan pendekatan hukum pidana yang selalu dipakai oleh orang tua murid, diperlukan solusi dan rekomendasi untuk pemecahan persoalan tersebut, diantaranya:
Pertama, Tindakan Legislatif. DPR perlu segera mengamendemen UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas untuk memberikan panduan yang jelas mengenai batasan disiplin pendidikan, dengan pengakuan eksplisit terhadap konteks budaya dan agama dalam pendidikan Indonesia.
Kedua, Pengembangan Institusional. Pemerintah perlu membentuk institusi khusus untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan pendidikan, dengan mandat untuk mempromosikan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.
Ketiga, Standar Profesional. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama perlu mengembangkan standar profesional dan program pelatihan yang komprehensif untuk pendidik, dengan penekanan pada metode disiplin modern dan kesadaran hukum.
Keempat, Keterlibatan Masyarakat, Pembuat kebijakan perlu memfasilitasi dialog masyarakat yang berkelanjutan untuk mengembangkan solusi yang tepat secara lokal yang menghormati nilai-nilai tradisional sambil menjunjung tinggi standar perlindungan anak.
Pada akhirnya, solusi untuk paradoks ini bukan dalam memilih antara tradisi atau modernitas, tetapi dalam menciptakan sintesis yang menghormati yang terbaik dari keduanya.
Indonesia memiliki kebijaksanaan dan sumber daya untuk mengembangkan model yang unik dan tepat untuk konteks nasional, yang dapat berfungsi sebagai contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa.
Transformasi ini memerlukan kesabaran, kebijaksanaan, dan itikad baik dari semua pihak. Namun, dengan kerangka hukum yang tepat, sensitivitas budaya, dan komitmen pada kepentingan terbaik anak-anak, Indonesia dapat menavigasi medan kompleks ini dengan sukses dan muncul dengan sistem pendidikan yang efektif sekaligus manusiawi.
***
*) Oleh : Husnul Hakim SY, MH., Dekan Fisip Unira Malang dan Pemerhati Kebijakan dan Hukum.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |